17 Oktober 1952: di pagi hari itu sekitar 5000 orang muncul di jalanan Jakarta. Pada pukul 8, mereka sudah berhimpun di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tak jelas siapa yang memimpin dan organisasi apa yang mengerahkan mereka, tapi yang mereka tuntut diutarakan dengan tegas: “Bubarkan Parlemen”. Kata sebuah poster, “Parlemen untuk Demokrasi, bukan Demokrasi untuk Parlemen”.
Tak lama kemudian mereka memasuki gedung perwakilan rakyat itu, menghancurkan beberapa kursi dan merusak kantin yang biasanya diperuntukkan bagi para legislator.
Dari sini, rombongan demonstran bergerak ke jalan lagi. Peserta makin bertambah besar. Akhirnya mereka, mencapai 3o ribu orang banyaknya, sampai ke Istana Negara. Mereka ingin menghadap presiden. Bung Karno, yang mengetahui apa yang dituntut para demonstran itu, akhirnya muncul. Dalam pidato singkat ia mengatakan: ia tak akan
membubarkan Parlemen. Ia tak ingin jadi diktator. Ia hanya berjanji pemilihan umum akan diselenggarakan segera.
Ringkas kata, Bung Karno menolak. Tapi rekaman ucapannya menunjukkan bahwa ia juga punya ketidaksukaan yang sama kepada “demokrasi liberal” yang dianggapnya sebagai cangkokan “Barat” itu. Di tahun 1959, ia membubarkan dewan perwakilan pilihan rakyat dan mengubah Indonesia dengan menerapkan “demokrasi terpimpin”.
Sistem ini kemudian berakhir di tahun 1966, ketika “Orde Baru” memperkenalkan format politik yang disebutnya “demokrasi Pancasila”—yang sebenarnya merupakan varian baru bagi “demokrasi terpimpin”. Boleh dikatakan, dalam “Orde Baru”, sebagian dari yang dikehendaki para penuntut pada tanggal 17 Oktober itu dipenuhi.
Kita tahu, seperti dicatat oleh Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, bahwa para perwira Angkatan Darat berada di belakang aksi hari itu. Sementara Bung Karno berpidato, militer memasang dua buah tank, beberapa panser, empat batang kanon yang ditujukan ke Istana: penegasan agar Presiden membubarkan Parlemen dan melikuidasi demokrasi liberal. Kita kemudian tahu, dalam “demokrasi Pancasila” yang ditegakkan Angkatan Darat, DPR memang dipilih secara reguler, tapi pada akhinya, kontruksi sang penguasa—dalam hal ini Suharto—yang menentukan. Berangsur-angsur, kekuasaan berkembang dari sifat “birokratik-otoriter” menjadi otokratik. Suharto mengulangi posisi Bung Karno sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”, dengan gelar yang berbeda.
Di tahun 1998, otokrasi Suharto itu rubuh. Indonesia mendapatkan “demokrasi liberal”—nya kembali. Satu dasawarsa kemudian, kita masih tampak percaya kepada demokrasi ini—jika itu berarti pemilihan umum yang reguler, partisipasi masyarakat pemilih lewat partai, pembentukan undang-undang melalui para legislator di parlemen, pengawasan kinerja kabinet dari sebuah lembaga negara yang dipilih rakyat. Tapi akan bertahankah kepercayaan itu?
Kita bisa menduga—melihat betapa korupnya para anggota DPR sekarang, melihat tak jelasnya lagi alasan hidup partai-partai, kecuali untuk mendapatkan kursi—Indonesia sedang memasuki sebuah masa, ketika rakyat—dengan hak penuh untuk memilih dan tak memilih—akan mencemooh, bahkan mencurigai, para pemegang peran dalam demokrasi parlementer yang ada.
Saya tak akan meramalkan bahwa “Peristiwa 17 Oktober” baru akan terjadi segera. Tapi saya kira siapa pun bisa melihat, kita akan hidup dengan harapan-harapan yang retak kepada demokrasi liberal. Dan tak akan mengherankan bila kita akan segera mendengar kecaman seperti yang pernah diutarakan novelis, Pemenang Nobel, Saramago: “Pemilihan umum telah jadi representasi komedi absurd, yang memalukan”.
Dalam pembicaraan saya hari ini, saya akan mencoba menunjukkan, bahwa disilusi seperti itu memang tak akan terelakkan. Persoalannya kemudian, sejauh mana dan dalam bentuk apa demokrasi bisa dipertahankan.
Demokrasi—sebagaimana kediktatoran—menjaga dirinya dari khaos. Ia jadi bentuk yang harus praktis dan terkelola. Ia dibangun sebagai sistem dan prosedur.
Tapi sebagai sebuah format, ia tak dapat sepenuhnya menangkap apa yang tak praktis dan yang tak tertata. Salah satu jasa telaah kebudayaan dan teori politik mutakhir ialah pengakuan terhadap pentingnya apa yang turah, yang luput tak tertangkap oleh hukum dan bahasa, yang oleh Lacan disebut sebagai le Reel (dalam versi Inggris, the Real), dan yang saya coba terjemahkan di sini sebagai “Sang Antah”.
Dengan itu sebenarnya ditunjukkan satu kekhilafan utama dalam pemikiran politik yang mengasumsikan kemampuan “representasi”. Pengertian “representasi” dimulai dari ilusi bahasa, bahwa satu hal dapat ditirukan persis dalam bentuk lain, misalnya dalam kata atau perwakilan. Ilusi mimetik ini menganggap, semua hal, termasuk yang ada dalam dunia kehidupan, akan dapat direpresentasikan.
Seakan-akan tak ada Sang Antah. Namun baik oleh teori “demokrasi radikal” yang diperkenalkan Laclau dan Mouffe, dengan menggunakan pandangan Gramsci, maupun oleh pemikiran politik dengan militansi ala Mao dalam pemikian Alain Badiou, kita ditunjukkan bahwa sebuah tata masyarakat, sebuah tubuh politik, adalah sebentuk scene yang tak pernah komplit. Senantiasa ada yang obscene dalam dirinya, bagian dari Sang Antah, yang dicoba diingkari. Tapi yang obscene—yang tak tertampung dan tak dapat diwakili oleh tubuh politik yang ada—justru menunjukkan bahwa scene itu, atau tata masyarakat yang kita saksikan itu, tak terjadi secara alamiah. Menurut Laclau dan Mouffe, tata masyarakat itu lahir dari hubungan antagonistis. Ia merupakan hasil perjuangan hegemonik. Itu sebabnya suatu tubuh politik yang tampak stabil mau tak mau dihantui oleh pertentangan—yang membuatnya hanya kwasi-stabil.
Dari pandangan seperti itu demokrasi, sebagai sebuah format, memang terdorong hanya merawat tubuh politik yang kwasi-stabil itu. Sebagai akibatnya, ia cenderung mengubah antagonisme dan perjuangan hegemonik itu jadi majal: demokrasi acapkali menghentikan proses politik dengan mendasarkan diri pada sebuah suara terbanyak atau sebuah konsensus. Dengan itu apa yang dianggap menyimpang, apa yang obscene, disingkirkan. Maka ia tampak sebagai sesuatu yang tak hendak membuka diri pada alternatif-alternatif baru.
Contoh yang segera dapat dilihat adalah Jepang; di sana, kekuasaan Partai Liberal Demokrasi (LDP) berlangsung hampir tak berhenti-hentinya. Hal yang sama dapat dikatakan tentang demokrasi Amerika. Hari-hari ini, justru di sebuah masa ketika suara untuk perubahan yang dibawakan Obama terdengar nyaring, sebetulnya tak tampak dahsyatnya “perubahan” yang disuarakannya.
Pernah saya katakan, demokrasi adalah sistem dengan rem tersendiri—juga ketika keadaan buruk dan harus dijebol. Pemilihan umum, mekanismenya yang utama, adalah mesin yang mengikuti statistik. Tiap pemungutan suara terkurung dalam “kurva lonceng”: sebagian besar orang tak menghendaki perubahan yang “ekstrem”. Statistik menunjukkan ada semacam tendensi bersama untuk tak memilih hal yang mengguncang-guncang. Statistik itu status quo.
Dalam haribaan “kurva lonceng”, Obama tak akan bersedia mengubah politik Amerika dengan yang baru yang menggebrak. Akan sulit kita menemukan perbedaan pandangannya tentang Palestina dari posisi Bush. Ia, yang harus mencari dukungan lobi Israel di Amerika, tak akan nekad bilang akan mengajak Hamas ke meja perundingan. Ia tak akan berani menampik sepenuhnya hak orang Amerika memiliki senjata api pribadi, meskipun korban kekerasan di negeri itu tak kunjung reda. Ia tak akan bertekad mengubah sikap orang Amerika yang cenderung memandang perang sebagai kegagahan patriotik, bukan kekejaman.
Seraya bersaing ketat dengan McCain, Obama—yang memproklamasikan diri sebagai pemersatu Amerika, negarawan yang akan menyembuhkan negeri yang terbelah antara “biru” dan “merah”—akan tampil sebagai si pembangun konsensus.
Tapi konsensus tak akan mudah jadi wadah bagi perubahan yang berani. Di Spanyol di tahun 1982, misalnya, ketika kediktatoran Franco sedang digantikan dengan demokrasi yang gandrung perubahan. Felipe Gonzales Marquez, waktu itu 40 tahun, memikat seluruh negeri. Partai Sosialisnya menawarkan lambang kepalan tangan yang yakin dan mawar merah yang segar. Semboyannya: Por El Cambio. Ia menang. Ia bahkan memimpin Spanyol sampai empat masa jabatan. Tapi berangsur-angsur, partai yang berangkat dari semangat kelas buruh yang radikal itu kian dekat dengan kalangan uang dan modal. Di bawah kepemimpinan Gonzales, Spanyol jadi anggota NATO dan mendukung Amerika dalam Perang Teluk 1991.
Sebagai tanda bagaimana demokrasi tak menginginkan yang luar biasa, Partai Sosialis menang berturut-turut. Mungkin itu indikasi bahwa “perubahan” pada akhirnya harus dibatasi oleh sinkronisasi pengalaman orang ramai. Di haribaan “kurva lonceng”, kehidupan politik yang melahirkannya kehilangan greget yang subyektif. Keberanian disimpan dalam laci.
Tapi mungkinkah sebuah masyarakat bisa berhenti dan proses politiknya tak tersentuh oleh waktu?
Pertanyaan retoris ini penting. Di dalamnya tersirat adanya harapan—di suatu masa ketika utopianisme Marxis digugat, tapi ketika pada saat yang sama pragmatisme ala Richard Rorty tampak tak memberikan daya bagi perubahan yang berarti.
Tapi untuk itu, memang diperlukan penyegaran kembali tentang apa arti “politik” sebenarnya.
Sebuah buku yang dengan amat baik memaparkan pemikiran politik kontemporer, Kembalinya Politik (Jakarta, 2008), menguraikan “dua muka yang terpisah” dalam pengertian “politik”:
Yang pertama adalah sisi di mana politik terjadi sebegitu saja dalam rutinitas kelembagaan dan perilaku actor-aktornya…… Yang kedua adalah politik yang diharapkan, yang tersimpan secara potensial, tidak teraktualisasi: politik sebagaimana diidamkan, yang tertekan di bawah instansi ketaksadaran.
Dalam pengantarnya, Robertus Robet dan Ronny Agustinus menunjukkan kemungkinan—atau malah kenyataan ketika demokrasi “telah membunuh politik” dan “menggantikannya dengan konsensus”.
Dengan kata lain, “politik” yang di-”bunuh” itu adalah politik sebagai proses perjuangan, bukan politik sebagai saling tukar kekuasaan dan pengaruh sebagaimana yang terjadi melalui pemilihan umum dan negosiasi legislatif dewasa ini di Indonesia.
“Politik” yang seperti itu sebenarnya hanya mengukuhkan tubuh sosial yang seakan-akan sepenuhnya direpresentasikan Parlemen. “Politik” yang seperti itu berilusi bahwa kita bisa mengabaikan Sang Antah. “Politik” yang seperti itu adalah bagian yang bersembunyi dari apa yang disebut Ranciere sebagai la police: struktur yang diam-diam mengatur dan menegakkan tubuh itu.
Di sini sebuah pemaparan selintas tentang teori Ranciere agaknya diperlukan.
La police itu (mungkin ada hubungan kata ini dengan “polis” sebagai negeri dan “polisi” sebagai penjaga ketertiban) bersifat oligarkis. Tubuh sosial mengandung ketimpangan yang tak terelakkan; selamanya ada yang kuat dan ada yang lemah, yang menguasai dan dikuasai.
Tapi la police itu tetap saja tak bisa membentuk sebuah satuan sosial yang komplit. Di dalam hal ini, pemikiran Ranciere juga menunjukkan bahwa satuan itu kwasi-stabil sebenarnya. Sebab bahkan la police tak akan bisa mengabaikan, bahwa yang kuat hanya kuat jika ia diakui demikian oleh yang lemah—meskipun dengan mengeluh dan marah. Dengan kata lain, si kuat diam-diam mengasumsikan adanya posisi dan potensi si lemah untuk memberi pengakuan. Bagi Ranciere, itu berarti nun di dasar yang tak hendak diingat, ada kesetaraan antara kedua pihak.
Di situ kita menemukan bagaimana sebuah negeri, polis, hidup: ada la logique du tort. Ada sesuatu yang salah dan sengkarut, tapi dengan begitu berlangsunglah sejarah sosial. Di dalam “logika” itu, ketegangan terjadi, sebab hirarki yang membentuk masyarakat justru mungkin karena mengakui kesetaraan. Ketegangan dalam salah dan sengkarut itulah yang melahirkan konflik, guncangan pada konsensus, dan polemik yang tak henti-hentinya. Ranciere mengakui, selalu ada sebuah arkhe, sebuah dasar untuk membenarkan timpangnya distribusi tempat dan bagian dalam masyarakat, tapi ia menunjukkan bahwa arkhe itu selamanya bersifat sewenang-wenang.
Dari itu terbit la politique: sebuah pergulatan. Ia bukan seperti aksi komunikasi ala Habermas: di arena itu tak ada tujuan untuk bersepakat; di medan itu yang hadir bukanlah sekadar usul dan argumen yang berseberangan, tapi tubuh dan jiwa, “perbauran dua dunia”, “di mana ada subyek dan obyek yang tampak, ada yang tidak”.
Agaknya yang tak tampak itulah yang menyebabkan la politique, atau politik sebagai perjuangan, mendapatkan makna sosialnya. Sebab yang menggerakkan adalah mereka yang bukan apa-apa, yang tak punya hakikat dan asal usul untuk menang.
Walhasil, selalu akan ada ketegangan antara la police dan la politique. Sebuah tubuh sosial akan bergerak, tak mandeg, dalam ketegangan itu. Di sini Ranciere memperkenalkan istilah lain, le politique, untuk menyebut proses mediasi antara kekuatan yang menjaga demokrasi sebagai format dan politik sebagai perjuangan ke arah kesetaraan.
Berbeda dari Badiou, Ranciere—yang menyebut keadaan demokrasi liberal sekarang sebagai “pasca-demokrasi”—masih menaruh kepercayaan akan peran demokrasi parlementer dan kemampuan perundang-undangan dalam perjuangan ke keadilan.
Tapi Ranciere bukanlah orang yang menganggap bahwa demokrasi parlementer dengan sendirinya adil. “Politik” sebagai perjuangan, “politik” sebagai la politique, itu sesuatu yang tak secara rutin terjadi. Bahkan jarang terjadi. Demikian pula, tanpa menyebut saat demokratik sebagai “kejadian” (l’evenement) yang luar biasa, Ranciere menganggap dalam sistem demokrasi yang ada, saat demokratik sejati tak selamanya didapatkan.
Dengan memakai pemikiran Ranciere, saya berharap dapat menunjukkan bahwa disilusi terhadap demokrasi liberal adakah sesuatu yang sah dan harus dinyatakan.
Tuntutan akan kesetaraan—dan dalam pengertian yang lebih luas: keadilan—adalah tuntutan yang tak akan habis-habisnya. Ia lahir dari apa yang tak hendak dilihat oleh sistem yang ada. Ia lahir dari yang obscene, dari yang turah dari representasi, ia adalah gaung Sang Antah yang tak tertampung.
Tapi haruskah kita menghancurkan demokrasi, karena menganggap bahwa demokrasi semata-mata format, bukan sebuah proses pergulatan, bukan arena la politigue? Jalan itu ada: “nihilisme aktif” dalam pengertian Simon Critchley, ketika ia menguraikan pendiriannya tentang “etika komitmen” dan “politik perlawanan” dalam Infinitely Demanding (Verso, 2008). Nihilisme aktif inilah yang dilakukan misalnya oleh teror Al Qaedah—yang pada gilirannya juga tak menumbangkan demokrasi liberal, bahkan memperkuatnya: makin kukuhnya aparat keamanan negara merupakan peneguhan dari la police.
Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan. Jalan yang ditempuh tak bisa dirumuskan sebelumnya; selalu diperlukan keluwesan untuk memilih metode, baik melalui perundang-undangan atau justru melawan perundang-undangan, baik melalui partai ataupun melawan partai.
Artinya, tiap kali kita membiarkan diri untuk didesak oleh panggilan akan keadilan yang tak pernah akan membisu.***
Catatan editor: Naskah ini dibacakan sebagai pidato dalam Nurcholis Madjid Memorial Lecture II yang berlangsung pada 23 Oktober 2008 di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina. Judul awal naskah ini adalah Demokrasi dan Disilusi, yang atas permintaan Goenawan Mohamad sendiri kemudian diubah menjadi Demokrasi dan Kekecewaan sewaktu naskah pidato ini diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) dan Yayasan Paramadina. Naskah yang tayang di website ini diambil dari buku itu tadi.
Selain judul, sedikit perubahan kecil juga dilakukan pada dua titimangsa: yaitu 17 Oktober 1953 [kalimat pertama] dalam naskah pidato dan naskah buku, dikoreksi menjadi 17 Oktober 1952 dan tahun 1958 [paragraf keempat] dalam naskah pidato dan naskah buku dikoreksi menjadi 1959.



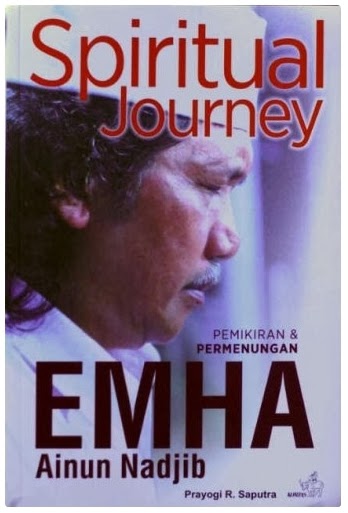
 15.38
15.38
 adi rahman
adi rahman


