Beberapa hari saja sehabis Mao mangkat. Negeri Cina diguncang gempa. Beberapa saat sehabis Nehru wafat, sungai Gangga konon meluap.
Takhayul memang membisikkan, ada hubungan antara hilangnya seorang besar dan resahnya alam. Tuhan lebih tahu kaitan-kaitan kosmis. Tapi di dalam banyak masyarakat manusia, seorang pemimpin besar memang tak jauh dari citranya yang “memangku bumi”, “memaku alam”, “memelihara buana” – citra yang terungkap misalnya dalam pelbagai gelar kerajaan Jawa.
Seorang pemimpin yang sebesar itu kuasanya, akhirnya, menjadi andalan tunggal bagi stabilnya kehidupan bersama: kata “memangku” dan “memaku” menunjukkan itu. Ia serba bisa, serba kuasa. Pelbagai keputusan penting maupun kurang penting berasal hanya berasal dari jari telunjuk atau ujung lidahnya. Tapi dengan itu pula tampak, bagaimana masyarakat yang andalannya Cuma itu sebenarnya bukanlah masyrakat yang stabil: tak banyak, di dalam sejarah, orang yang sanggup menjadi paku jagat, jadi seorang Mao atau seorang Nehru. Pada saat seorang besar mati, sendi-sendi pun goyah.
Tapi kematian adalah hal yang tak terelakkan. Soalnya kemudian adalah: apa yang harus dilakukan.
Ada sebuah catatan ahli antropologi tentang sebeuah negeri yang terletak di wilayah Danau Victoria, di Afrika. Negeri yang disebut Bunyoro itu bukan negeri primitif. Eli Sagan, dalam At The Dawn of Tyranny, menyebutnya “masyarakat yang kompleks” : di sana, pertautan sosial tak lagi didasarkan kepada persamaan keluarga. Kesetian dan ketakutan kepada raja merupakan bentuk yang telah melewati ikatan sedarah-daging.
Pada tahap itu, umumnya semacam rasa cemas umumnya merundung kesatuan itu, karena ketenraman lama, yang dulu dirasakan orang dalam pertalian keluarga, kini tak ada lagi. Dari suasana kejiwaan itu lahirlah satu bentuk kekuasaan yang agresif, dan sekaligus defensif:tirani. Di pucuknya berperan seorang yang diharapkan hampir maha kuasa, mahamenentramkan, memaku dan memangku bumi.
Maka, ketika seorang raja Bunyoro meninggal, kesatuan itu pun seperti lepas pegangan. Orang mengharapkan munculnya seorang mahakuasa baru. Suatu cara yang penuh darah pun dilangsungkan. Para putra raja dibiarkan berperang, bunuh membunuh, hingga satu yang tak terkalahkan. Dialah yang dinobatkan.
Namun, upacara tak Cuma berakhir disitu. Pada tahap terakhir, sang perdana menteri, bamurago, mendatangi seorang pangeran muda yang tak ikut berperang. Kepadanya sang bamurago mengumumkan bahwa rakyat telah memilihnya untuk naik takhta. Si pangeran muda terpaksa mau. Sementara itu, raja yang sebenarnya datang menghadap, disertai para pembesar. Tapi ia tampak menyajikan upeti. Maka, sang bamurago pun pura-pura menyuruhnya agar mengambil persembahannya. Ketika raja yang sebenarnya pergi, perdana menteri itu pun berkata kepada si pangeran muda, “Mari lari, saudaramu itu pergi menjemput pasukan.” Lalu sang bamurago pun sang pangeran ke sebuah kamar. Bocah itu dicekik sampai mati.
Untuk apa ritus seganas itu? Dalam analisa Sagan, baik perang saudara maupun pembunuhan atas raja-rajaan itu adalah ekspresi, yang mengemukakan bahwa raja sebenarnya sesuatu yang rapuh. Ia tampil sebagai elemen mahakuasa, tapi sebenarnya diakui pula bahwa dalam prakteknya, ia tak bisa demikian. Pengakuan seperti itu, pada saat yang sama, sangat merisaukan. Maka, si bocah yang pura-pura dijadikan raja itu harus dibunuh. Bukan saja karena ia sebuah unsur palsu, tapi juga karena ia – yang memang lemah – hadir sebagai cemooh terhadap pretensi besar itu: pretensi kemahakuasaan.
Kemahakuasaan raja memang yang jadi ideal, tetapi sebenarnya keyakinan akan kemahakuasaan itu tipis betul. Suatu saat, setiap saat, keyakinan itu bisa punah. Dan ketika rasa ragu dan cemas itu begitu menyelubungi jiwa, orang pun menjadi kian ganas. Mereka ingin meniadakan kebimbangannya sendiri. Mereka membunuh segala lambang kelemahan, tiap tanda ketidakkuasaan. Di Bunyoro, sekali setahun orang melakukan upacara pencekikan seorang pangeran kecil.
Tapi tak seorang pun akhirnya bisa mengelak dari keterbatasan – biarpun ia seorang raja yang bebas berbuat apa pun. Para pemimpin yang penuh karisma, dengan kekuasaan penuh di tangan mereka, pada saatnya harus pergi, dengan atau sonder gempa bumi.
Namun, jika masyaraktnya beruntung, dari sana akan tumbuh suatu “tubuh politik” yang lain: sebuah kebersamaan yang punya pemimpin-pemimpin rutin, sebuah masyarakat yang mengakui kemungkinan sang raja untuk khilaf dan, suatu saat, tak akan di sana lagi.
17 Oktober 1987



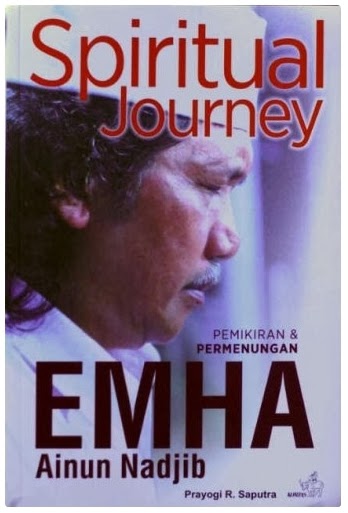
 23.39
23.39
 adi rahman
adi rahman