”Hello, darkness . . .”. Kita dengar di latar belakang Simon and Grafunkel menyanyi, lirih seperti melamun. Dan ketika si anak muda berzina dengan ibu pacarnya, tetangga papi-maminya, kita tahu juga lanjutan kekosongan sebuah lingkungan kelas menengah yang seperti sedang kena anastesi.
Lalu si anak pun memberontak. Selamat tinggal hidup borjuis.
Tapi itu Amerika pada tahun 60-an, Amerika yang sedang muak dengan segala yang materialistis dan kelas menengah. Amerika dalam dasawarsa 80-an kini adalah Amerika lain: Amerika-nya Tom Cruise yang terkesima mendengar bahwa “Rakus itu bagus” dalam Wall Street. Atau Amerika dalam film Risky Business, ketiko konon Tom Cruise jadi seorang murid sekolah menengah yang membiarkan seorang pelajar membuka bordil di rumah orang tuanya. Perempuan itu pun dengan bersemangat tanpa rasa bersalah, tanpa ragu – bekerja. “What a capitalis,” kata Tom Cruise setengah bingung setengah kagum.
Maka kata seorang penulis pada masa The Graduate bisnis dianggap sama dengan prostitusi, pada masa Tom Cruise tak perlu dibedakan mana bisnis dan mana prosititusi.
Zaman memang berubah – dan tak Cuma di Amerika Serikat. Jika seorang wartawan New York bernama John Taylor bercerita tentang “kultur kekayaan dan kekuasaan pada tahun 1980-an (dalam Cirsus of Ambition), jika ia bicara tentang mahajutawan Donald Trump yang menghancurkan ukiran bersejarah di sebuah gedung tua yang dibelinya, jika ia bercerita tentang para yuppies dan “pangeran Wall Street” yang hidup gemerlap dengan uang yang bukan miliknya, kita juga – di Jakarta – merasa cerita seperti ini adalah rekaman tentang sebuah gaya yang menular.
Pemeo di Jakarta yang ering kita dengar, “uang punya kuasa” kini seakan digaris-bawahi tebal-tebal kekayaan sudah jadi ukuran tunggah yang sah. Dulu orang bisa merasa tetap utuh harga dirinya tanpa punya benda-benda besar. Seorang guru bisa tetap merasa seperti seorang ksatria: gajinya kecil tapi ia merasa terhormat karena mengabdi kepada sesuatu yang lebih agung. Kini siapa lagi yang demikian?
Ya, zaman memang berubah. Ada masanya para nabi dan para demonstran mengecam kekayaan. Kecaman itu tak selamanya berarti mengandung niat hendak mensakralkan kemiskinan. Tapi kini nampaknya orang bukan saja hendak menyatakan sikap kaya yang tanpa rasa berdosa. Orang bahkan ingin mensakralkan: kekayaan yang berlimpah setidaknya bisa saja dikaitkan dengan ibadah.
Di Amerika, Bakker, penginjil televisi itu, sempat mengumpulkan uang begitu rupa, dan punya rumah begitu rupa, dan kandang anjing begitu rupa, bersar dan ber-AC. Ia akhirnya dijatuhi hukuman sebagai penipu, namun para pengikutnya tetap (juga setelah ia dibuktikan bersalah) melihat si bapa penginjil ada di jalan Tuhan.
Dan Bakker tak sendiri. Hal yang serupa bisa terjadi di Indonesia, dengan sedikit variasi. Bukankah orang Islam juga pernah dianjurkan untuk “bekerja buat dunia seperti hendak hidup selama-lamanya dan bekerja untu akhirat seperti hendak mati besok”, sering dengan kesimpulan bahwa tak ada salahnya dapat dua jenis surga sekaligus, dalam arti punya dua Baby Benz dan dua gelar haji?
Saya tak tahu adakah ini hanya satu “mode” yang melintas, sebuah demam zaman, ataukah ini tanda akhir yang menampakkan bahwa manusia memang “cuma begitu” : makhluk yang menginginkan surga sebanyak-banyaknya, kini dan nanti.
Yang pasti, keperluan setiap individu untuk harta, benda, waktu, kesempatan, apalagi kekuasaan, akhirnya akan terbentur pada satu batas: jutaan individu lain juga lambat atau cepat menghendaki hal-hal yang sama. Dengan kata lain, kehidupan sosial dan ekonomi dan politik akan selalu terdiri dari pergulatan untuk “peroleh bagian”. Ada yang akan menang dan ada yang akan kalah.
Bahaya terbesar akan tiba bila tanda kemenangan jadi hanya satu, dan ukuran kemenangan jadi hanya tunggal, ketika kekayaan materi tak bisa dipisahkan lagi dari kekuasaan atau dari kehormatan sosial, bahkan dari standar perilaku dan harga diri. Sebab dalam keadaan seperti itu, siapa yang kalah di satu hal akan kalah di segala, dan tamat.
Goenawan Mohammad # 4 November 1989



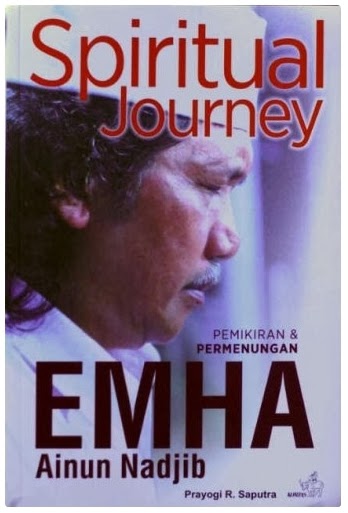
 22.00
22.00
 adi rahman
adi rahman