Tentu, saya sendiri tak tahu persis bagaimana tanah air menjelang 1945. tapi mungkin kita bisa membayangkannya: suatu masa ketika pikiran besar dan kecil telah ramai bergulat. Harapan-harapan, untuk sebuah negeri yang bebas, mekar. Pemikir dan penyair sibuk, juga asyik. Dan Chairil pun menulis puisi: begitu besar, begitu kurang ajar.
”Aku suka pada mereka yang berani hidup”, tulisnya, setengah kagum, tentang para pemuda yang berjaga malam seperti prajurit, dan bermimpikan kemerdekaan. ”Aku suka pada mereka yang masuk menemu malam”.
Dan jika dalam malam itu ada bahaya, juga dosa, setan, atau sifilis, tak perlu risau. Binal adalah satu pernyataan – sekaligus risiko – dalam kemerdekaan. Kita tak akan tunduk. Tak ada sensor, tak ada ketakutan, tak ada sejarah, batas administrasi, doktrin agama, dan segala yang dianggap membatasi.
Bahkan Tuhan, dalam kemahakuasaannya, ia terima sebagai tekanan. Sebuah sajak yang ditulisnya pada 29 Mei 1943, misalnya, Di Mesjid, melukiskan pertemuannya dengan Tuhan dalam kiasan yang sangat berbeda dengan metafora Amir Hamzah dari tahun 30-an. Amir Hamzah berbicara tentang kerinduan; Chairil bicara tentang sebuah peperangan. ”Ini ruang”, tulisnya tentang tempat peribadatan itu, ”Gelanggang kami berperang”.
Memang, beberapa tahun kemudian ia menulis sajak Doa yang menggetarkan itu: “Tuhanku/Dalam termangu/Aku masih menyebut namaMu”. Tapi ia juga, pada kumpulan sajak yang sama, bisa mencemooh harapan manusia akan surga yang lazim, “yang kata Masyumi + Muhammadiyah bersungai susu/dan bertabur bidari beribu”. Sebab, kata Chairil meragukan surga. Ia memilih hidup yang kini, yang baginya lebih bergairah.
Beli Koes Plus Golden Hits, Vol. 4 di Amazon
Ia, dalam umur 20-an, memang biasa bicara angkuh, cerdas cekatan, kocak dan kadang menohok. Tapi ia bicara di awal tahun 40-an, ketika sebuah bangsa harap-harap cemas menantikan dirinya merdeka. Hidup di ambang arena yang menjanjikan banyak hak. Hidup juga masih mencari bentuk institusi-institusinya sendiri.
Artinya, tak ada yang memberangus Chairil. Ia sendiri tak merasa terancam. Masyumi + Muhammadiyah tak mengerahkan massa untuk menyerbu atau menuntut, bahkan setahu saya tak ada pernyataan “kami tersinggung”. Juga tak ada kanwil deperdag dan kanwil depdikbud, tak ada laksusda dan kadit binmas dan akronim-akronim lain yang, dari pelbagai meja persegi, mengetahui soal keselamatan masyarakat dan karena itu merasa tahu betul perkara sajak. Indonesia di masa Chairil adalah Indonesia yang lain dari yang kini kita kenal.
Setelah sekian tahun merdeka, Indonesia kini telah jadi sebuah negeri yang rasanya semakin tahu sulitnya sebuah kemerdekaan. Banyak yang mengharap, beberapa yang mendapat, sebagian yang kecele. Pelbagai kelompok sosial tampil. Semuanya merasa wajib dicatat, untuk dapat tempat. Perebutan untuk ke atas pun tak dapat dihindarkan. Kemerdekaan telah membuka pintu untuk itu. Lagi pula, berada di bawah betapa sumpeknya, betapa terancamnya.
Bahwa bentrokan dan kemarahan dan ketersinggungan sering terjadi, juga represi, siapa yang bisa menyalahkan? Siapa yang bisa disalahkan?
Orang Yunani, dengan mitologinya yang aneh, mungkin akan mengatakan bahwa kemerdekaan punya nemesisnya sendiri. Kemerdekaan punya pembalasannya – yakni kerisauan dan kecemasan. Seperti bertahun-tahun yang lalu dikatakan ahli psikologi Erich Fromm, manusia sering takut untuk merdeka – dan kembali ke kongkongan.
Chairil agaknya tahu juga, apa sisi lain kemerdekaan itu. Dalam sebuah sajaknya buat Gadis Rasid, ia bicara tentang “bangsa muda menjadi”, yang “baru bisa bilang ‘aku’”. Di sebelah sini ada daun-daun hijau, padang lapang dan anak-anak kecil tak bersalah. Tapi di sebelah sana “angin tajam kering, tanah semata gersang, pasir bangkit mentanduskan”. Dan di antara kedua sisi itulah, antara suasana terbuka yang segar dan ancaman ketandusan pikiran, sang penyair merasa terapit. “Kita terapit, cintaku – mengecil diri . . . “
Tapi tak mandek. Ia bahkan mengajak terbang, the only possible nonstop flight, terbang mengenali gurun, sonder ketemu, sonder mendarat. “Mari kita lepas, kita lepas jiwa mencari jadi merpati”. Yang penting bukanlah suatu arah, melainkan keberanian menjelajah. Yang penting bukanlah satu konklusi, melainkan eksplorasi.
Merpati itu mungkin capek kemudian, dan jatuh. Dan tahu, bahwa “ada yang tetap tidak diucapkan,/sebelum pada akhirnya kita menyerah”, seperti ditulisnya di ujung sebuah sajak yang mengharukan menjelang ia meninggal. Adakah itu kearifan,atau sebuah putus asa, untuk kita semua, kini ?
Goenawan Mohammad # 1 Februari 1986



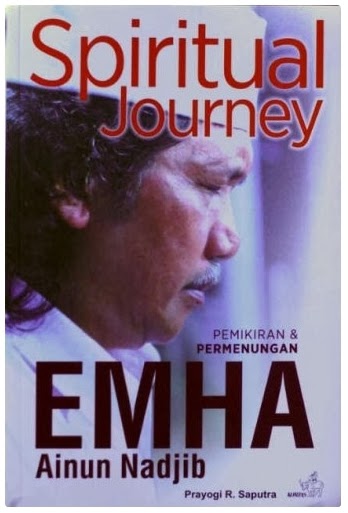
 21.47
21.47
 adi rahman
adi rahman
