Misalkan pada tahun 2000 Amerika Serikat runtuh, Jepang amblas ke laut dan semoga "negeri maju" raib dari muka bumi. Akan lebih baiklah negeri-negeri berkembang? Atau akan lebih buruk?
Bagi "Kaum Merah", persentuhan antara sebuah negeri miskin dengan negeri kaya hanya akan mencelakakan si melarat. Bantuan luar negeri, modal asing, keikutsertaan Bank Dunia dan IMF, dianggap memasukkan negeri-negeri miskin ke dalam suatu sistem internasional yang menyebabkan mereka jadi - atau tetap jadi - kurang berkembang. Kadang-kadang hal memang disengaja, kata "Kaum Merah", karena niat untuk menghisap kepentingan sepihak. Tetapi kadang-kadang juga karena tak sengaja: mengkaitkan mengkaitkan diri dengan negara-negara kaya, kata "Kaum Merah" pula, menjadikan sebuah negara miskin kian sulit serta mustahil untuk memilih cara pembangunannya sendiri.
Dan hasilnya? "Kaum Merah" menunjuk: yang memperoleh kenikmatan dari kontak negeri kaya itu hanya selapis kecil manusia di negeri miskin: para pemegang kekuasaan politik yang mungkin dapat komisi atau Sogok, serta para pemegang kekuasaan ekonomi yang sudah terlatih dengan omong Inggris, kelincahan manajemen modern dan akal panjang abad ke-20, hal-hal yang diperlukan dalam bisnis dengan orang asing. Mereka yang bukan perjabat dan yang berada jauh dari kancah ekonomi modern, akan tergeser. Garis perbedaan sosial pun membelah dahsyat. Walhasil, ketika sebuah negeri berkembang melakukan integrasi dengan sistem internasional, yang terjadi ialah suatu disintegrasi dalam tubuh negeri itu sendiri.
Benarkah? Setidaknya sebagian dari argumen itu perlu didengar. Tapi baiklah kini kita simak pendapat "Kaum Biru". Menurut "Kaum Biru", perkembangan sebuah negeri miskin menjadi kurang miskin (atau kaya dan "maju") berjalan secara lurus: selangkah demi selangkah, sebuah negeri naik, dari keadaan mandek sampai dengan lepas landas. Dalam proses itu, negara yang sudah kaya dapat menyediakan hal-hal yang dperlukan untuk perkembangan alias alias pembangunan itu: modal, devisa atau mata uang yang bisa laku buat berdagang di pasar dunia, ketrampilan, teknologi. Jangan salah paham. "Kaum Biru" juga setuju bahwa bantuan luar negeri dari utara ke selatan itu bukan sekadar kedermawanan. Negeri kaya punya kepentingan buat membantu negara miskin - misalnya buat memperluas pasar atau menyediakan tenaga buruh yang murah.
Dan "Kaum Biru" pun menunjuk contoh kemajuan yang terjadi dengan mengesankan di
Tentu saja uraian di atas agak menyederhanakan soal. Tapi harus diakui, bahwa hari-hari ini kita melihat banyak "Kaum Biru" yang ketawa dan "Kaum Merah" yang nampak terbata-bata. Bukan saja karena negeri-negeri seperti Korea Selatan dan Singapura ramai-ramai dipuji oleh para ahli dan para pelancong, tapi juga karena kisah sukses mereka mulai kian banyak diikuti negeri lain.
Sejak tahun 1966,
Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa “Kaum Merah” yang terdengar lebih gagah berani dan lebih mengetuk hati ketimbang mengetuk perut kini kurang didengar? Saya tak tahu jawabannya. Mungkin diseantero negeri sosialis akhirnya orang manggut-manggut kepada apa yang pernah dikatakan oleh Joan Robinson: “Kenestapaan akibat dihisap oleh para kapitalis bukan apa-apa bila dibandingkan dengan kenestapaan karena sama sekali tak dihisap”. The misery of being exploited by capitalists is nothing compared to the misery of not being exploited at all.
Betapa



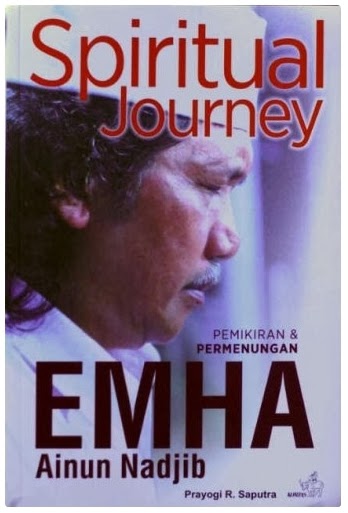
 21.59
21.59
 adi rahman
adi rahman