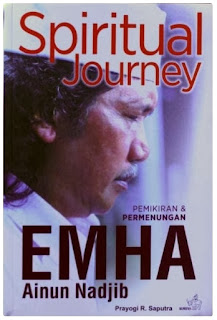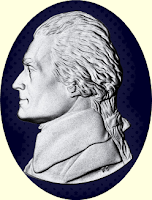Asal Usul Istilah "Nation State"
Ilmu politik identik dengan kepengurusan negara atau dikenal dengan istilah "nation" atau "state". Apakah "nation" atau "state" itu sebuah institusi? Penguasa? Otoritas? Sistem nilai? Atau Apa?

Free Ebook - Ebook Gratis
ABC's Political Economy. Comprehensive coverage of all politics sciences,themes and term. Buku panduan politik tingkat lanjut. Lengkap dan mendalam. Jangan baca kalau anda tidak ingin "melek politik"

SANG PUJANGGA
Jatuh cinta membuat orang jadi pujangga. Terbitnya matahari dapat diubahnya bak emas kemilau yang menerangi dunia hingga bayangan pun malu tercipta di balik benda-benda.

PILAR-PILAR SPIRITUALITAS CAK NUN
Siapa yang tak kenal Cak Nun ? Para pemerhati budaya, sastra dan pergerakan pasti mengenalnya. Sepak terjangnya dapat dilacak hingga ke awal 1970an hingga era kontemporer yaitu momen dimana rezim Soeharto roboh. Banyak yang tidak sepemikiran, namun tidak sedikit pula yang mensejajarkannya dengan Gus Dur bahkan Wali Songo. Memang selevel itukah Cak Nun ?

Senin, 04 November 2013
PILAR-PILAR SPIRITUALITAS EMHA AINUN NADJIB
 19.33
19.33
 adi rahman
adi rahman
Jumat, 01 November 2013
Yours Forever
 19.24
19.24
 adi rahman
adi rahman
Sabtu, 26 Oktober 2013
Display
 19.17
19.17
 adi rahman
adi rahman
Rabu, 12 Desember 2012
kanvas
 22.04
22.04
 adi rahman
adi rahman
Ia mati tak punya apa-apa dalam usia 37, tapi di tahun 1987 ini, hampir seabad kemudian, sebuah lukisannya dilelang dan dibeli oleh perusahaan asuransi Yasuda di Tokyo dengan Rp 65 milyar. Itu kurang lebih sama seperti harga 500 buah mobil Mercedez Benz. Majalah Eksekutif pun menyebut lelang lukisan Bunga Matahari karya Van Gogh di London sebagai ”lelang terbesar abad ini”. Riwayat Van Gogh memang penuh kejadian yang layak untuk sebuah biografi hebat, dan tak aneh bila 30 tahun yang lalu Kirk Douglas memainkannya (dengan sejumlah bumbu Holywood) dalam Lust for Life. Tapi apa yang luar biasa? Orang telah terbiasa dengan cerita anekdotis tentang seniman yang hidup gila-gilaan dan aneh dan berantakan: kita sudah menonton Amadeus atau mendengar tentang Chairil Anwar yang makan sate mentah dan mati muda.
Seniman, agaknya, telah menjadi semacam keistimewaan – punya semacam privilese untuk tak dinilai dengan ukuran orang biasa. Saya tak tahu persis darimana dan sejak kapan semua itu berasal. Kakek nenek kita di kampung dulu rasanya tak pernah mengenal seniman sebagai kategori tersendiri. Buku Umar Khayam yang menarik, Semangat Indonesia, satu rekaman selintas tentang kehidupan kesenian rakyta di Indonesia, menunjukan bagaimana orang membuat seni (di Nias, di Bali, di pedalaman Irian) bukan hanya untuk ”keindahan” melainkan bagian dari alat kerja dan upacara – tanpa tepuk tangan.
Tapi mengapa Bunga Matahari Van Gogh ternyata dibeli orang dengan Rp 65 milyar? Kenapa orang tak datang saja ke museum Van Gogh di Amsterdam, yang necis dan penuh cahaya di musim panas, atau membeli reproduksinya – cukup bagus – dengan harga tak sampai Rp 10 ribu?
Jawabnya, mungkin: ada manusia yang memang tak cuma kepengin benda-benda yang akhirnya bisa diraih oleh banyak orang, betapapun mahalnya. Ia juga menginginkan sesuatu yang oleh seorang ahli ekonomi disebut sebagai ”kekayaan olirgakis”, yakni hal-hal yang, saking langkanya akhirnya hanya bisa dimiliki oleh satu dua pribadi, walaupun orang lain mampu membelinya. Ironi Van Gogh ialah bahwa ia, yang bermula denga melukis petani miskin di Borinage, kemudian menjadi unsur dalam kekayaan olirgakis itu.
Tapi untunglah: keindahan tak cuma hadir dalam sebuah lukisan seharga sekian puluh milyar. Kita toh bisa melihat ada yang indah pada etalase toko Esprit di Singapura, stempel karet di kaki lima Malioboro, sampul kaset musik jazz Chandra Darusman – pada segala sesuatu yang sehari-hari, yang sementara, yang sepele. Bukankah di Bali juga keindahan didapat pada patung keramik yang besok mungkin pecah?
Memang – dan sejumlah seniman, dengan semangat besar, mengukuhkan itu, ketika mereka mengumumkan diri sebagai Gerakan Seni Rupa Baru, dan dalam sebuah pameran di Taman Ismail Marzuki yang menarik, memaparkan iklan dan stiker dan kalender dan kaus oblong dari sembarang pojok. Tak berarti ada sesuatu yang baru dalam pendirian mereka. Penulis kritik seni Bambang Budjono, misalnya, bisa menyebutkan bahwa di tahun 1938 sebuah pameran para ”ahli gambar” Indonesia, diikuti juga oleh pelukis poster bioskop – suatu bukti, agaknya bahwa, di Indonesia, sejak dulu, orang memang bisa berkesenian tanpa merasakannya sebagai suatu privilese. Orang bisa berkesenian dengan cara yang sangat ringan: sebagian dari hidup yang biasa dan tidak menakjubkan.
Keindahan, karena itu, memang bukan monopoli elite –terutama elite sosial, yang di Indonesia kini nampak masih gugup dan canggung mencari selera. Apa yang indah bagi ”orang sekolahan” tak bisa dipaksakan sebagai indah bagi orang pinggiran. Tapi dengan sikap toleran dan demokratis sekalipun tak berarti keindahan tak menyembunyikan hierarkisnya sendiri, apapun kriterianya: lukisan ”Gerilya” S. Soedjojono bagi saya lebih menggetarkan ketimbang lukisan ”Jaka Tarub” Basuki Abdullah. Iklan dalam majalah Interview Andy Warhol lebih memukau ketimbang iklan ribut pabrik kaset ”JK Records” dalam Tempo. Singkat kata, yang satu punya tingkat yang berbeda dibanding yang lain. Di sini, tak ada perlakuan yang sama. Di sini, apa yang disebut ahli sosiologi Daniel Bell sepuluh tahun yang lalu sebagai ”The democratization of genius” – lahir dari semangat ”kerakyatan” dalam kesenian barat yang meledak di tahun 1960-an – menjadi hal yang mustahil.
Sebab ”demokratisasi kejeniusan” berarti peniadaan kejeniusan itu sendiri. Sementara itu, kejeniusan adalah bagian yang tak bisa ditolak dalam proses ketika manusia menciptakan kebudayaan. Kejeniusan mendorong kita ke pintu yang lebih luas. Kejeniusan itu bernama Van Gogh, yang ingin melukis terus, intens, sampai gila, seraya bertanya, ”Buat apa?”
Mungkin ia tak tahu apa jawabnya. Tapi kita tahu apa yang diberikannya kepada kita, lewat kepedihannya. Dan itu bukan sebuah kanvas seharga Rp 65 milyar.
Goenawan Mohammad # 27 Juni 1987
Senin, 12 November 2012
bhargawa
 22.02
22.02
 adi rahman
adi rahman
Di dekatnya, dengan setia, Radheya menyediakan diri jadi bantal bagi gurunya. Ia memangku kepala yang besar dan perkasa dengan rambut panjang yang terjalin keras itu. Ia merasakan kebahagian yang dalam – bahagia seorang yang ingin mengabdi, ingin menghormati – karena tahu; yang ia jaga adalah ketentraman seorang yang selama ini membagikan kepadanya ilmu dan kepiawaian.
Dan Resi Bhargawa pun tertidur berjam-jam, dan Radheya duduk menyangganya berjam-jam, tak bergerak, membisu. Hanya hatinya tidak membisu. Hari itu menjelang hari terakhirnya berlatih dengan bagawan yang termasyhur itu.
”Terima kasih, guru, kau telah terima penghormatanku – telah kau terima diriku. Aku tak pernah melupakan hari itu, tujuh tahun yang lalu, ketika aku berbuat pertama kalinya mengetuk pintu asramamu dan kau bertanya, ”Siapakah engkau, anak muda?”
”Aku tahu, guru, tuan tak hanya menginginkan sebuah nama. Tuan menanyakan sebuah niat, dan sebuah riwayat – jalan panjang yang menyebabkan aku, seorang dari keluarga tak ternama, datang dan menyatakan akan belajar kepadamu. Aku bergetar, guru, engkau begitu dahsyat. Dan aku tahu aku tak akan pernah bisa menjawab.
”Sebab, aku hanya tahu cerita ini: Seorang remaja telah datang dari pedalaman. Ia dibesarkan oleh seorang sais kereta yang konon bukan ayahnya sendiri – sebab anak itu tumbuh dengan keingan lain yang tak pernah dikhayalkan orang tuanya. ”Engkau memang cuma anak pungut kami, buyung”, kata wanita yang selam ini menjadi ibunya dengan terisak-isak, ”mimpimu bukan mimpi kami.”
”Jadi, siapakah dia, guru? Yang ia tahu pasti ia diberi nama Radheya, dengan hasrat yang ganjil dan tinggi: menjadi seorang pemanah ulung, seperti yang didengarnya dari cerita Ibu, tentang perang dan para bangsawan. Lalu pada suatu hari ia datang ke guru termasyhur itu, Resi Durna. Tapi ditolak. Ia cuma anak seorang suta – bukan kelas yang berhak dengan ilmu peperangan.
”Maka, ia pun berdiri, Resi, di depan gerbang asramamu, dengan lutut menggeletar. Dan ia harus memberikan keterangan. Hari itu kurasakan, dalam pertanyaan pertamamu, ujung pisau yang meraba sarafku. Tapi akhirnya engkau menerimaku. Tak ada riwayat yang lebih bersinar-sinar dalam diriku, selain menjadi muridmu, menerima ilmumu, menerima kepercayaanmu . . . .
”Meskipun aku telah menjustaimu. Hari itu kukatakan kepadamu, ”Hamba anak seorang brahmana jauh di pedalaman Hastina’, dan kau percaya. Kau berikan ilmu kepadaku dengan kepercayaan itu. Kau jadikan aku murid utamamu sampai tuntas, tanpa kau tahu kebohonganku.
”Maafkan, aku, guru. Aku bukan anak Brahamana. Aku tak tahu aku anak siapa – jika benar aku hanya anak pungut seorang suta. Toh aku tak bisa mengaku berasal dari kalangan ksatria yang kau benci itu – orang-orang yang kau anggap sesat, orang-orang yang membakari hutan pertapaan lalu membangun kerajaan di atas mayat dan ketakutan. Aku bukan anak musuhmu, guru, meskipun aku tak datang dari kaummu. Aku adalah aku, Radheya, muridmu. . . . ”
Dan berjam-jam sang guru tertidur, dan berjam-jam sang murid mengabdi. Sampai menjelang senja, sesuatu terjadi. Seekor serangga ganas memagut paha anak muda itu. Darah menetes. Rasa sakit menguasai seluruh tubuhnya. Ia tak ingin menyebabkan gurunya – yang dikasihinya itu – terbangun. Kesakitan itu, baginya, adalah bagian dari tugasnya, dari baktinya.
Tapi darah menetes ke muka Bhargawa. Sang resi terbangun. Dilihatnya apa yang terjadi: muridnya, dengan wajah pucat menahan sakit, dan tubuhnya demam, tetap duduk seperti berjam-jam yang lalu, tak bergeming. Bhargawa pun meloncat bangun dan memegang bahu Radheya yang menggigil. ”Kau sakit, kau terkena racun. Apa yang terjadi?”
Radheya menceritakan apa yang terjadi. Dan Bhargawa mendengarnya dengan takjub – dan sesuatu tba-tiba tersirat dalam wajah anak ini, yang teguh, yang angkuh menahan kepedihan, yang seakan-akan mencemooh penderitaan yang bagi orang lain tak akan tertahankan. ”Wajah itu”, Bhargawa tiba-tiba menyimpulkan, seakan-akan sebuah mimpi buruk baru saja mengilhaminya. ”Sikap itu – keangkuhan itu – ”. Ia kenal. Anak muda yang dihadapinya ini mengingatkannya kepada wajah para ksatria, musuhnya, yang pernah roboh ia kalahkan, tapi tak menyerah.
Tanpa berkata-kata, ia pun meninggalkan Radheya di bawah pohon itu. Murid itu pun pelan-pelan berjalan ke arah asrama, tanpa ia merasa sesuatu telah hilang dari gurunya. Malam itu Bhargawa memang yakin: kecurigaannya selama ini tentang Radheya memang terbukti. Anak itu, yang telah diberinya pelbagai ilmu oerang yang tinggi, berasal dari kalangan musuh. Mungkin ia mata-mata . . . .
Ketika pagi datang, sang guru mengusir sang murid. Ia kecewa dan ia mengutuk ketika anak itu mengaku selama ini ia menjustainya. Baginya justa adalah justa. Juga dari seorang yang belum bisa menjawab siapa dirinya.
Goenawan Mohammad # 11 April 1987